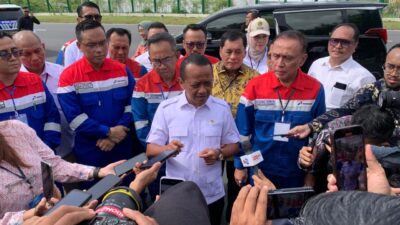Di Amerika kemarin itu saya bertemu empat wanita istimewa.
Yang satu bernama Mel, di Oakland, tidak jauh dari rumah masa kecil Kamala Harris. Aslinyi Banyuwangi. Tamatan Madrasah Aliyah. Tidak pakai jilbab. Kaca mata hitamnya dipadu dengan jaket ketat yang keren. Dia sangat menjaga diri agar hanya makan makanan yang pasti halal.
Bagi Mel, lebih baik hanya makan sayur daripada makan daging ayam yang tidak tahu disembelih dengan cara apa (Baca Disway: Bismillah Karnaval).
Tapi Mel tidak sok halal. Dia tidak menunjukkan ekspresi wajah negatif ketika orang di sebelahnyi makan apa saja.
Bahkan dia berusaha menutupi orientasi keras halalnyi itu dengan cara yang sangat sopan: “saya vegetarian”.
Suaminyi orang bule. Asal Prancis. Pun suaminyi yang meninggal beberapa tahun lalu: juga orang kulit putih.
Mel ikut saya ke acara makan malam di Palo Alto –kawasan startup di Silicon Valley.
Dalam perjalanan, di dalam mobil, saya dengar percakapan Mel dengan wanita di sebelahnyi yang lagi mengemudi.
“Boleh nggak saya pindah kerja ke tempatmu,” tanya Mel.
“Boleh. Mulai minggu depan?”
“Jangan minggu depan. Saya masih mau urus anak saya dulu. Bagaimana kalau mulai bulan depan.”
“Boleh.”
“Berapa gajinya?”
“Mau kan USD 70 per jam?”
“Tidak bisa lebih tinggi?”
“Kita lihat dulu”.
“Tapi dikontrak paling tidak satu tahun lho ya.”
“Kok lama. Gak bisa tiga bulan saja?”
Terputus. Belum lagi pembicaraan selesai ada topik lain yang tiba-tiba harus dibicarakan.
Saya tahu Mel bukan wanita yang lagi menganggur. Dia sudah bekerja: juga di bidang IT. Tapi rupanya dia terus berusaha cari gaji yang lebih tinggi. Tawaran 70 dolar/jam (sekitar Rp 1 juta per jam) masih dia anggap kurang tinggi.
Itu pun Mel tidak mau lama-lama. Gaji Rp 1 juta/jam itu hanya batu loncatan. Meloncatnya pun cepat-cepat.
Kesan saya: betapa mudah cari pekerjaan di Amerika. Betapa ringan untuk memutuskan pindah kerja. Tidak ada perasaan khawatir apakah akan bisa dapat pekerjaan pengganti.
Setelah tiga hari di New York saya ke New Haven, Connecticut. Dua wanita ingin mengantar saya.
Yang satu mbak Sri. Asal Sragen. Suaminyi juga bule –asal Los Angeles. Sang suami ahli software. Sudah pensiun dari perusahaan raksasa bidang IT, IBM.
Mbak Sri menyesalkan mengapa saya tidak tidur di rumahnyi di dekat New York. Rumah yang, katanyi, enak untuk menulis buku. Di pinggir danau besar. Ada dua rumah di situ. Berdekatan. Saya, katanyi, bisa datang dan pergi kapan saja.
Kalau bosan di situ masih ada rumah lagi di Montana. Di pinggir taman hutan di dekat Kanada.
“Saya sudah beli tiket kereta api,” kata saya. “Tidak perlu diantar.”
Bukan berarti kami tidak bisa bertemu. Mbak Sri mengajak suami berkendara ke New Haven. Satu jam perjalanan. Kami pun ngobrol banyak hal sambil makan siang.
Bersama Mbak Sri dan suami.–
Di tengah makan ada info masuk: Mbak Dini juga ingin mengantar saya ke Hartford. Dia orang Demak, Jateng. alumnus Universitas Satya Wacana. S-2 dan S-3 nyi di Amerika.
Tapi Dini baru bisa berangkat agak sorean. Dia masih mengajar. Dia profesor linguistik Mengajar di Yale University –universitas papan atas di Amerika.
“Sampai ketemu di Hartford nanti malam,” kata Prof Dini.
Mbak Sri dan suami mengantar saya ke stasiun. Mobilnya Volvo. Masih agak baru. Sudah puluhan tahun saya tidak naik Volvo.
“Ini sudah jadi mobil China,” ujar sang suami. Perusahaan mobil Swedia terkemuka ini memang sudah dibeli Tiongkok.
Naik kereta api dari New Haven ke Hartford seperti dari Solo ke Yogyakarta. Keretanya lambat. Berhenti banyak kali. Jarak 80 km ditempuh dalam satu jam.
Caranya juga masih sangat kuno: kondektur mendatangi setiap penumpang. Setelah memeriksa tiket dia menempelkan kertas di atas tempat duduk. Itu tanda penumpang di kursi itu turun di stasiun mana.
Setiap kereta akan berhenti dia datangi penumpang di bawah kertas tempel itu. Waktunya turun. Lalu kertas yang dia tempelkan itu diambil.
Pun ketika kereta akan berhenti di stasiun Hartford. Dia datangi saya. “Di sini Anda turun”, katanyi. Lalu mencopot tempelan kertas di atas kepala saya.
Di Hartford saya bertemu wanita istimewa lainnya. Nisa. Pakai jilbab hitam. Asal Bontang, Kaltim. Masa kecilnya di Gang Alwi, Samarinda, tidak jauh dari rumah istri saya.
Nisa bisa berbahasa Banjar dan mengerti bahasa Bugis. Orang tuanya campuran Banjar-Bugis. Dia sudah lebih 10 tahun di Hartford –setelah pindah dari New York.
Suami Nisa dari Turkiye. Kampung suaminya di satu jam naik pesawat dari Istambul, ke arah Asia. Sang suami pengusaha bidang logistik.
“Di mana ketemu suami?”
“Di online.”
“Saat Anda masih tinggal di Bontang?”
“Iya. Saat masih di Bontang.”
Nisa punya anak satu. Cewek. Menjelang remaja. Cantik sekali.
Di Chicago ketemu satu wanita Indonesia lagi yang bersuamikan bule: Mayasari. Rumahnyi di Greenburg, Indiana. Di situ Maya buka restoran Indonesia. Juga mendirikan pabrik tempe.
Cita-cita Maya: pabrik tempenyi itu akan menggunakan artificial intelligent (AI). Maya memang ambil computer science saat kuliah di Purdue University, Indiana.
Sang suami orang pedalaman Indiana. “Petani,” kata Maya yang selalu merasa sebagai orang Bogor. Bapaknyi Sunda, ibunyi Sangihe.
Sang ayah pernah jadi kapolres Bogor. Sawah milik sang suami biasa-biasa saja luasnya: hampir 1000 hektare.
Maya dan Suami–
Maya mendapat penghargaan dari Pemda setempat. Pabrik tempenyi dianggap bisa menaikkan nilai tambah produk kedelai lokal.
Di kampung suaminyi itu mayoritas petani menanam kedelai. Nilai kedelai pasti naik kalau bisa jadi tempe. Maya pun dapat dana untuk pengembangan tempe.
Maya juga sudah mematenkan proses pembuatan tempe di Amerika. Termasuk teknik memproses air kran agar memenuhi syarat sebagai air yang bisa dipakai untuk membuat tempe.
—
Sang suami menanam kedelai, Maya hilirisasi kedelai. “Tempe bisa untuk toping mie goreng Indomie,” ujar Maya.
Itulah salah satu menu yang laris di resto “Mayasari” di Indiana.
Wanita Indonesia ternyata banyak juga yang pilih go global.(Dahlan Iskan)