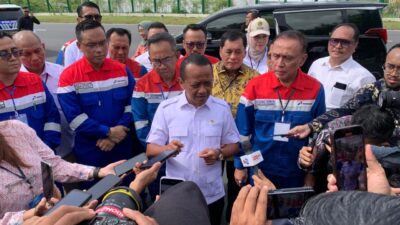Transisi energi melalui kebijakan biomassa Co-Firing, nampaknya masih harus melalui jalan panjang dan berliku. Persoalan ekonomi, dan lingkungan serta dukungan pemerintah yang minim jadi menghambat.
Dampak lingkungan dari aktivitas PLTU yang masih dominan menggunakan batu bara juga menjadi perhatian. Di tengah desiran ombak dan riuhnya kehidupan pesisir, nelayan-nelayan di Teluk Balikpapan kini menghadapi tantangan yang semakin berat.
Kehadiran perusahaan-perusahaan besar seperti PLTU Co-Firing Teluk Balikpapan, Petrosea, dan BCT tidak hanya mengubah wajah lingkungan, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup mereka.
Bilal, salah seorang nelayan, merasakan dampak langsung dari aktivitas perusahaan-perusahaan ini. “Kami hanya diberi jarak 100 meter dari jeti perusahaan. Jika itu yang ditetapkan, kami mau ke mana?” keluh Bilal dengan nada pasrah.
Jarak tersebut seakan mengurung mereka dalam area yang semakin menyempit, membuat aktivitas menangkap ikan menjadi semakin sulit.
Ia merasa bahwa semua perusahaan yang beroperasi di sekitar mereka memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil tangkapan nelayan.
Meskipun PLTU Co-Firing menggunakan campuran biomassa dari limbah kayu, sebagian besar bahan baku yang diandalkan tetap batu bara. Ini menjadi sumber keprihatinan bagi Bilal dan rekan-rekannya. Setiap hari, mereka harus menghirup asap pembakaran dan debu batu bara yang melayang dari cerobong asap PLTU.
“Debu itu dari boiler yang dibakar, terbang ke udara, dan dibawa angin utara ke sini. Kami hanya bisa pasrah dengan nasib,” katanya.
Bau batu bara yang menyengat seolah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Masyarakat pesisir merasa terpaksa untuk tetap beraktivitas, meskipun khawatir dengan dampak polusi yang mengintai.
“Kalau kami takut dengan baunya, kami tidak bisa beraktivitas di laut. Mau tidak mau, kami harus menerima keadaan ini,” ungkapnya.
Limbah batu bara yang dihasilkan oleh PLTU juga menjadi ancaman serius bagi hasil tangkapan nelayan. Nelayan-nelayan di Teluk Balikpapan, yang berada di ring satu, jelas menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut.
Bilal mengakui bahwa ia belum mengetahui dengan pasti jarak antara tempat tinggalnya dan perusahaan-perusahaan tersebut, tetapi satu hal yang jelas: nelayan adalah pihak yang merasakan dampak langsung.
“Ini bukan hanya masalah dari PLTU, tetapi dari semua perusahaan. Jika limbah minyak terlihat jelas, limbah batubara dari PLTU tidak tampak alirannya ke mana,” tegasnya.
Minim Dukungan Pemerintah Daerah
Implementasi kebijakan Co-Firing di PLTU Teluk Balikpapan juga dihadapkan pada minimnya dukungan dari pemerintah daerah.
Anggi dari Forest Watch Indonesia (FWI) menegaskan, program ini berjalan secara top-down dari PLN tanpa keterlibatan pemerintah setempat dalam pengawasan dan mitigasi dampak lingkungan.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait kesiapan mitigasi risiko, terutama dalam pengawasan lingkungan dan keamanan operasional.
Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam kebijakan energi ini terlihat kurang harmonis dan tidak terintegrasi, berdampak pada ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan kebutuhan atau kesiapan di daerah.
Misalnya, pemerintah daerah belum memiliki regulasi dan perangkat yang cukup untuk menangani aspek pemantauan lingkungan, seperti Rencana Kelola Lingkungan (RKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
“Sejalan dengan target PLN untuk mencapai bauran energi hingga 5-10 persen dari biomassa di 52 PLTU pada tahun 2025, co-firing tampaknya dicanangkan secara ambisius,” ujarnya.
Kendati demikian, Anggi menilai bahwa program ini terkesan dipaksakan tanpa memperhitungkan kesiapan sumber daya manusia, kemampuan pemerintah daerah, maupun kesiapan perangkat kebijakan di tingkat lokal.
Seharusnya, penyusunan kebijakan energi ini mengutamakan prinsip partisipatif dengan proses-proses Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), di mana publik diajak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan melalui penelitian dan konsultasi yang lebih luas.
Implementasi co-firing sejauh ini juga masih menghadapi masalah dalam pemenuhan bahan baku biomassa.
Karena kurangnya sumber bahan baku yang stabil, PLN mulai mempertimbangkan berbagai alternatif, termasuk penggunaan lahan tidur.
Namun, pemanfaatan lahan ini harus sesuai dengan tata ruang dan prinsip-prinsip konservasi lingkungan, seperti perlindungan sumber air dan tanah.
Potensi ancaman ekologi dari program co-firing ini dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru di sektor lingkungan, misalnya risiko alih fungsi ruang terbuka hijau (RTH) untuk memenuhi kebutuhan bahan baku biomassa.
Anggi juga menyebut adanya kekhawatiran akan potensi alih fungsi lahan mangrove di kawasan Teluk Balikpapan, yang memiliki peran penting dalam ekosistem pesisir. Program ini, jika dilaksanakan tanpa evaluasi yang matang dan monitoring yang intensif, dapat mengancam keberlanjutan ekosistem lokal di Balikpapan.
Secara keseluruhan, kurangnya koordinasi antara PLN dan pemerintah daerah, ditambah dengan pelaksanaan yang belum optimal, membuat program co-firing ini menghadapi banyak tantangan di lapangan.
Anggi menyarankan agar kebijakan energi yang melibatkan pemanfaatan biomassa dilakukan melalui pendekatan yang lebih berkelanjutan, melibatkan berbagai pihak secara aktif, serta mempertimbangkan kapasitas daerah agar hasilnya tidak hanya sekadar memenuhi target bauran energi.
“Tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam di Kalimantan Timur,” tutupnya.(salsa/arie)